Jurnalis Kontributor: Gadis
Jurnalperempuan.com-Jakarta. “Apa arti ‘multikulturalisme’ ketika malah mengkotak-kotakkan? Apa arti keberagaman, yang atas nama itu yang satu bisa menyerang yang lain?” Komentar Nawal el Saadawi ini dikutip Maria Hartiningsih dan Ninuk M. Pambudy (Kompas, 4/12/2006) untuk mendefinisikan multikulturalisme.
“Multikulturalisme”—sebuah wacana relatif baru di Indonesia yang disebut-sebut bergulir sejak reformasi 1998—sebenarnya secara umum mengacu pada pemahaman akan keberagaman budaya. Namun, dalam bukunya yang berjudul Multiculturalism and ‘The Politics of Recognition’ (1990) Charles Taylor memperluas pemikiran politik multikulturalisme dengan memperjelas multikulturalisme itu sebagai bentuk dorongan kepentingan politik kaum minoritas atau kelompok-kelompok subaltern atau kelompok kelas kedua yang mana gerakan-gerakan feminisme termasuk di dalamnya.
Anehnya, diskusi dan peluncuran buku tentang Multikulturalisme, antara lain buku Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia dan Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa, tidak membahas tentang isu perempuan secara khusus.
Diskusi yang terselenggara antara Yayasan Interseksi dan Yayasan Tifa ini hanya fokus pada karakter negara, modernitas dan hukum yang represif dan diskriminatif pada masyarakat lokal dan adat serta implementasi hukum internasional yang tidak kontekstual pada tingkat lokal. Padahal diskursus tentang multikulturalisme semestinya juga memasukkan isu-isu kesetaraan gender ke dalamnya.
Sejauh ini, benak kita kemudian bertanya di manakah keberpihakan gagasan multikulturalisme dalam suara perempuan?
Sayang memang ketika diskusi dan peluncuran buku yang diadakan Kamis (4/9), di Jakarta ini tidak mampu menyorot adanya paradoks dalam multikulturalisme. Wilayah yang menjadi topik diskusi barulah seputar wilayah publik dan bukannya wilayah privat, di mana perempuan sering ditempatkan. Budaya patriarkis yang masih kental, ketika bersentuhan dengan isu perempuan, hanya akan menjadi alat justifikasi praktik opresi perempuan.
Dalam kajian Gramsci tentang subaltern atau kelompok kelas kedua, yaitu perempuan, tenaga-tenaga kerja, para buruh tani, termasuk kalangan minoritas atau kelompok-kelompok inferior berada di luar sistem hegemonik masyarakat disebabkan oleh kemiskinan atau diskriminasi etnis. Mereka kadangkala tidak direpresentasikan karena dieksklusikan oleh mereka—para intelektual yang secara umum berada dalam sistem hegemonik dominan (Rodriguez, "From Representation to Recognition" The Latin American Subaltern Studies Reader).
Dari penjelasan tersebut dan diandaikan standar hegemonik adalah negara, maka terlihat jelas bahwa etnis minoritas ataupun perempuan dapat dikatakan sama-sama menempati posisi sebagai golongan inferior. Bahkan, kajian subaltern atau kajian kelas kedua ini dapat melihat adanya represi perempuan oleh kelompok adat.
Keterbukaan dalam isu multikulturalisme jelas tidak terpatok pada isu-isu marjinalisasi kaum adat saja, melainkan melebar juga ke dalam wacana perempuan dan keberagaman identitasnya dalam wilayah adat di Indonesia. Lagipula, sungguh pendek rasanya perjuangan diskursus multikulturalisme jika harus terbentur paradoks dalam gagasan itu sendiri. Sebagaimana lazimnya realitas, keberagaman identitas itulah yang akan membangun keberagaman budaya itu sendiri.*
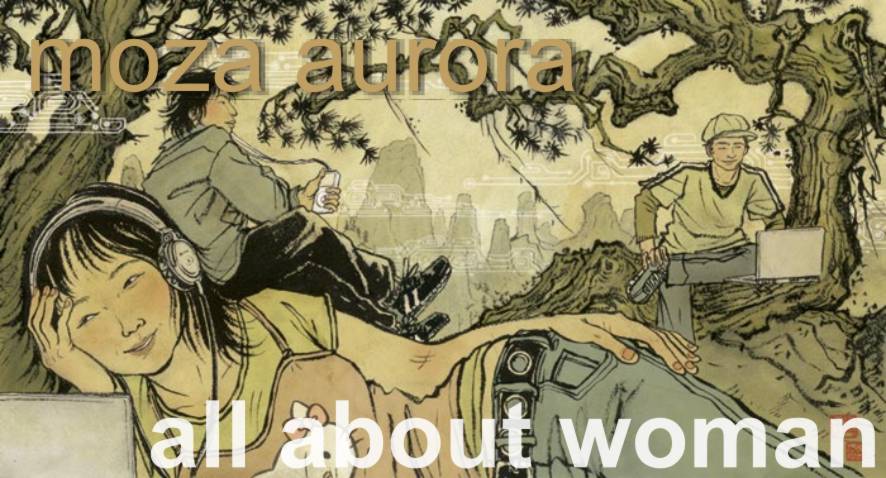
Tidak ada komentar:
Posting Komentar